COP29: Mengapa Negara Penghasil Energi Fosil yang Otoriter Jadi Tuan Rumah
Ini tahun ketiga berturut-turut konferensi iklim diadakan di negara-negara penghasil bahan bakar fosil yang dianggap otoriter.
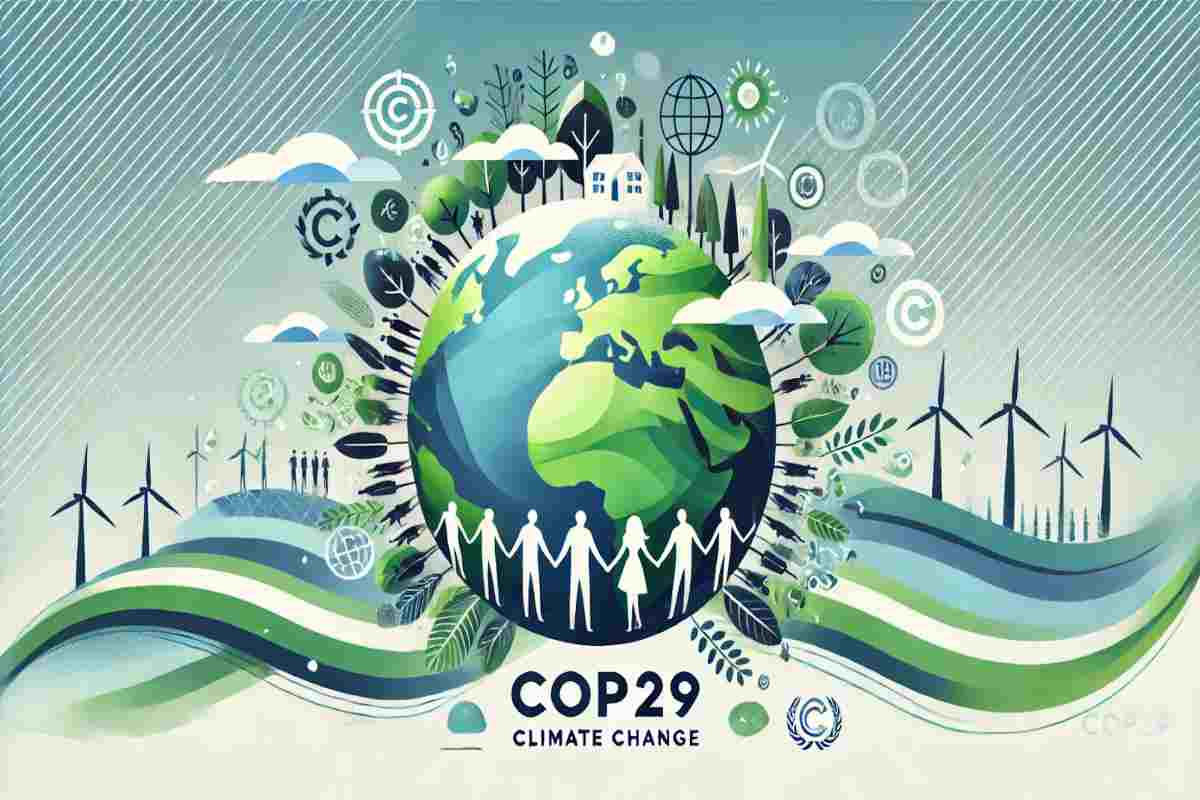
Context.id, JAKARTA - Pada November 2024 ini, di Baku, ibu kota Azerbaijan tengah berlangsung Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP29). Dipilihnya negara ini menjadi tuan rumah konferensi internasional yang membahas soal pemanasan global dan perubahan iklim tentu menjadi hal yang menarik.
Pasalnya, Azerbaijan adalah salah satu negara penghasil migas terbesar dunia, bahan bakar fosil yang dianggap sebagai penyebab terbesar krisis iklim dan pencemaran udara.
Masalahnya, sebelum Azerbaijan, ada Dubai di Uni Emirat Arab dan Sharm El Sheikh, Mesir yang menjadi tuan rumah. Artinya ini tahun ketiga berturut-turut konferensi iklim diadakan di negara-negara otoriter penghasil bahan bakar fosil.
Ya, COP27 dan COP28 diadakan di dua negara Timur Tengah itu. Pemilihan negara-negara penghasil minyak yang juga dianggap dipimpin rezim otoriter sebagai tuan rumah COP menjadi tanda tanya.
Apakah ini bagian dari upaya untuk menyadarkan mereka atau ada hal lain? Mengingat bagaimana pengaruh politik domestik dan kepentingan ekonomi mereka dapat memengaruhi arah kebijakan iklim dunia.
BACA JUGA
Melansir Reuters, negara-negara Timur Tengah dan juga pecahan Uni Soviet seperti Azerbaijan selama ini dikenal dan identik sebagai negara otoriter.
Negara-negara itu biasanya kekuasaan terpusat pada satu individu atau sekelompok elit yang memiliki kontrol kuat atas kebijakan domestik mereka dan dianggap sering mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi.
Pengaruh besar negara-negara seperti Rusia, China, dan beberapa negara di Timur Tengah dalam sektor energi mempengaruhi lebih dari sekadar kebijakan domestik mereka, tapi juga iklim internasional.
Negara-negara ini tidak hanya produsen utama bahan bakar fosil, tetapi juga menjadi pemain penting dalam pasokan mineral langka yang vital untuk energi terbarukan, seperti yang diperlukan dalam kendaraan listrik dan teknologi energi hijau lainnya.
China, misalnya, mendominasi pasar global untuk mineral kritis, dan merupakan negara terdepan dalam manufaktur kendaraan listrik.
Sementara itu, Rusia tetap menjadi eksportir besar bahan bakar fosil, meskipun sanksi internasional pascainvasi Ukraina membatasi akses mereka ke pasar global.
Dalam konteks ini, tuan rumah konferensi iklim di negara-negara dengan rezim otoriter sering kali mencerminkan dinamika geopolitik yang lebih luas, di mana kepentingan ekonomi dan politik negara-negara tersebut tidak hanya mencakup keuntungan dari sumber daya alam, tetapi juga pengaruh yang mereka miliki dalam menentukan arah kebijakan global.
Di tengah perundingan iklim internasional, negara-negara otoriter sering kali memiliki posisi yang lebih kuat dalam menghalangi kemajuan.
Ini karena pemerintah mereka dapat memobilisasi sumber daya dengan cepat dan tanpa banyak kontrol institusional yang menghalangi keputusan cepat.
Pada COP28 di Dubai, misalnya, meskipun ada kesepakatan mengenai transisi dari energi fosil, negara-negara seperti China tetap bergeming pada kebijakan mereka yang mendukung penggunaan batu bara, yang sangat penting bagi ekonomi mereka.
Rusia, meski terisolasi di kancah politik internasional, tetap dapat memanfaatkan COP27 untuk mempromosikan agenda energi nuklir dan memperkuat hubungan dengan negara-negara berkembang, yang bergantung pada energi murah dan teknologi energi terbarukan non-Barat.
Di COP29, Reuters memperkirakan Rusia kemungkinan akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menegaskan kembali posisinya dalam geopolitik energi dan meredam tekanan internasional terhadap kebijakan iklimnya.
Berkembangnya kepercayaan pada otoritarianisme
Banyak yang menganggap negara-negara dengan penghasil minyak yang juga otoriter dapat lebih efektif dalam merespons bencana iklim dan mengimplementasikan teknologi hijau dalam skala besar.
Dalam beberapa tahun terakhir, negara-negara seperti China, Laos, dan Vietnam telah berhasil meluncurkan proyek-proyek energi terbarukan besar-besaran dari tenaga surya hingga nuklir tanpa ada hambatan sedikitpun.
Hal yang berbeda tentunya saat ide-ide itu diterapkan di negara-negara demokratis.
Keunggulan ini memberikan legitimasi tambahan bagi rezim otoriter di mata publik, karena dianggap lebih mampu mengatasi masalah iklim dibandingkan negara demokrasi yang terjebak dalam perdebatan politik.
Hal ini berpotensi mengarah pada penguatan otoritarianisme sebagai bentuk pemerintahan yang lebih dapat diandalkan dalam menghadapi krisis besar.
Namun, semakin banyaknya negara-negara otoriter yang terlibat dalam perundingan iklim juga menimbulkan tantangan bagi negara-negara demokratis.
Harus diakui juga banyak negara demokratik yang berkomitmen terhadap Perjanjian Paris dan transisi energi, tapi kalah posisi dengan industri fosil yang juga banyak di negara-negara itu.
Di sisi lain, negara-negara otoriter dengan kekuatan politik yang terkonsentrasi dapat lebih mudah mengelola perubahan besar, seperti penutupan industri bahan bakar fosil dan transisi ke energi terbarukan, meskipun dengan cara yang lebih represif.
China, misalnya, telah berhasil memasarkan teknologi energi terbarukan ke negara-negara berkembang, menjadikannya alternatif utama bagi kerjasama energi dengan negara-negara Barat.
Ini memperlihatkan bagaimana pengaruh geopolitik dapat berperan dalam merancang ulang arsitektur kerja sama internasional mengenai perubahan iklim.
Saat COP29 dimulai, tantangan besar yang dihadapi dunia adalah bagaimana melibatkan negara-negara raksasa minyak ini dalam upaya global untuk mengurangi emisi karbon dan membatasi pemanasan global hingga 1,5 derajat Celsius.
Negara-negara ini, yang masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil untuk pertumbuhan ekonomi mereka, berisiko menghambat kemajuan yang telah dibuat dalam perundingan internasional sebelumnya.
POPULAR
RELATED ARTICLES
COP29: Mengapa Negara Penghasil Energi Fosil yang Otoriter Jadi Tuan Rumah
Ini tahun ketiga berturut-turut konferensi iklim diadakan di negara-negara penghasil bahan bakar fosil yang dianggap otoriter.
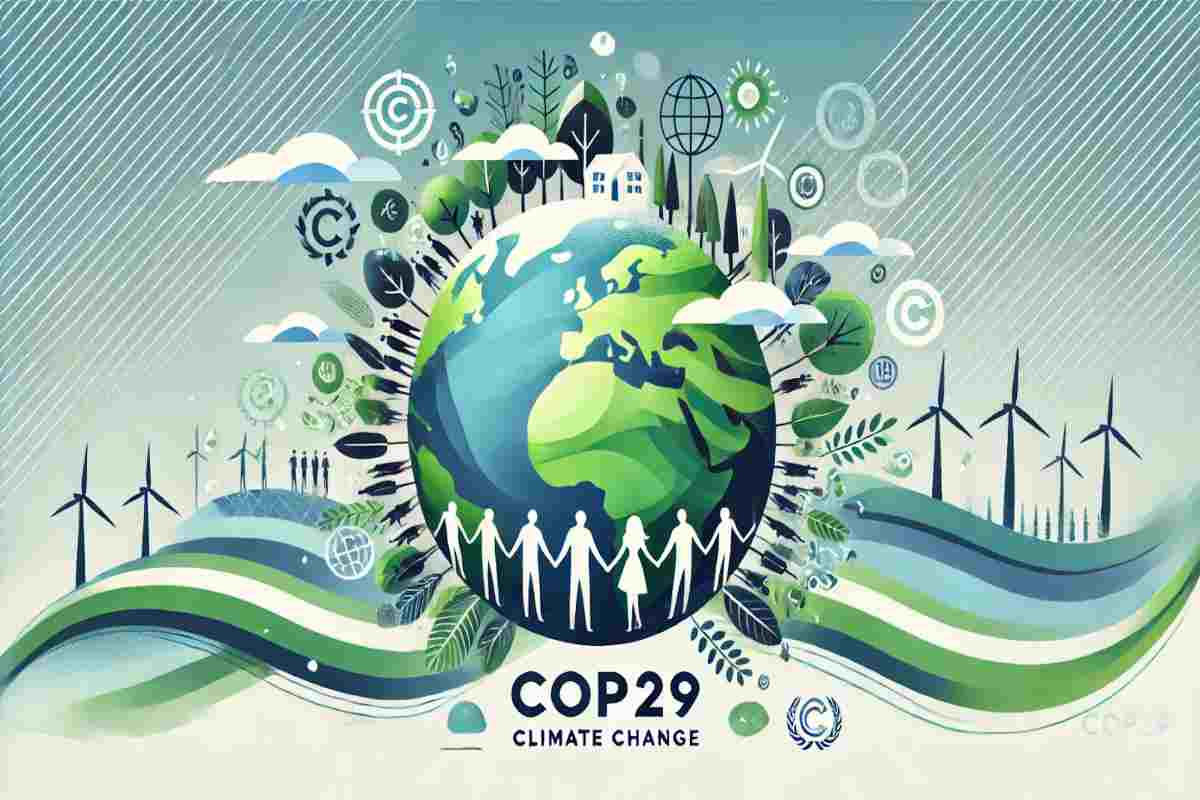
Context.id, JAKARTA - Pada November 2024 ini, di Baku, ibu kota Azerbaijan tengah berlangsung Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP29). Dipilihnya negara ini menjadi tuan rumah konferensi internasional yang membahas soal pemanasan global dan perubahan iklim tentu menjadi hal yang menarik.
Pasalnya, Azerbaijan adalah salah satu negara penghasil migas terbesar dunia, bahan bakar fosil yang dianggap sebagai penyebab terbesar krisis iklim dan pencemaran udara.
Masalahnya, sebelum Azerbaijan, ada Dubai di Uni Emirat Arab dan Sharm El Sheikh, Mesir yang menjadi tuan rumah. Artinya ini tahun ketiga berturut-turut konferensi iklim diadakan di negara-negara otoriter penghasil bahan bakar fosil.
Ya, COP27 dan COP28 diadakan di dua negara Timur Tengah itu. Pemilihan negara-negara penghasil minyak yang juga dianggap dipimpin rezim otoriter sebagai tuan rumah COP menjadi tanda tanya.
Apakah ini bagian dari upaya untuk menyadarkan mereka atau ada hal lain? Mengingat bagaimana pengaruh politik domestik dan kepentingan ekonomi mereka dapat memengaruhi arah kebijakan iklim dunia.
BACA JUGA
Melansir Reuters, negara-negara Timur Tengah dan juga pecahan Uni Soviet seperti Azerbaijan selama ini dikenal dan identik sebagai negara otoriter.
Negara-negara itu biasanya kekuasaan terpusat pada satu individu atau sekelompok elit yang memiliki kontrol kuat atas kebijakan domestik mereka dan dianggap sering mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi.
Pengaruh besar negara-negara seperti Rusia, China, dan beberapa negara di Timur Tengah dalam sektor energi mempengaruhi lebih dari sekadar kebijakan domestik mereka, tapi juga iklim internasional.
Negara-negara ini tidak hanya produsen utama bahan bakar fosil, tetapi juga menjadi pemain penting dalam pasokan mineral langka yang vital untuk energi terbarukan, seperti yang diperlukan dalam kendaraan listrik dan teknologi energi hijau lainnya.
China, misalnya, mendominasi pasar global untuk mineral kritis, dan merupakan negara terdepan dalam manufaktur kendaraan listrik.
Sementara itu, Rusia tetap menjadi eksportir besar bahan bakar fosil, meskipun sanksi internasional pascainvasi Ukraina membatasi akses mereka ke pasar global.
Dalam konteks ini, tuan rumah konferensi iklim di negara-negara dengan rezim otoriter sering kali mencerminkan dinamika geopolitik yang lebih luas, di mana kepentingan ekonomi dan politik negara-negara tersebut tidak hanya mencakup keuntungan dari sumber daya alam, tetapi juga pengaruh yang mereka miliki dalam menentukan arah kebijakan global.
Di tengah perundingan iklim internasional, negara-negara otoriter sering kali memiliki posisi yang lebih kuat dalam menghalangi kemajuan.
Ini karena pemerintah mereka dapat memobilisasi sumber daya dengan cepat dan tanpa banyak kontrol institusional yang menghalangi keputusan cepat.
Pada COP28 di Dubai, misalnya, meskipun ada kesepakatan mengenai transisi dari energi fosil, negara-negara seperti China tetap bergeming pada kebijakan mereka yang mendukung penggunaan batu bara, yang sangat penting bagi ekonomi mereka.
Rusia, meski terisolasi di kancah politik internasional, tetap dapat memanfaatkan COP27 untuk mempromosikan agenda energi nuklir dan memperkuat hubungan dengan negara-negara berkembang, yang bergantung pada energi murah dan teknologi energi terbarukan non-Barat.
Di COP29, Reuters memperkirakan Rusia kemungkinan akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menegaskan kembali posisinya dalam geopolitik energi dan meredam tekanan internasional terhadap kebijakan iklimnya.
Berkembangnya kepercayaan pada otoritarianisme
Banyak yang menganggap negara-negara dengan penghasil minyak yang juga otoriter dapat lebih efektif dalam merespons bencana iklim dan mengimplementasikan teknologi hijau dalam skala besar.
Dalam beberapa tahun terakhir, negara-negara seperti China, Laos, dan Vietnam telah berhasil meluncurkan proyek-proyek energi terbarukan besar-besaran dari tenaga surya hingga nuklir tanpa ada hambatan sedikitpun.
Hal yang berbeda tentunya saat ide-ide itu diterapkan di negara-negara demokratis.
Keunggulan ini memberikan legitimasi tambahan bagi rezim otoriter di mata publik, karena dianggap lebih mampu mengatasi masalah iklim dibandingkan negara demokrasi yang terjebak dalam perdebatan politik.
Hal ini berpotensi mengarah pada penguatan otoritarianisme sebagai bentuk pemerintahan yang lebih dapat diandalkan dalam menghadapi krisis besar.
Namun, semakin banyaknya negara-negara otoriter yang terlibat dalam perundingan iklim juga menimbulkan tantangan bagi negara-negara demokratis.
Harus diakui juga banyak negara demokratik yang berkomitmen terhadap Perjanjian Paris dan transisi energi, tapi kalah posisi dengan industri fosil yang juga banyak di negara-negara itu.
Di sisi lain, negara-negara otoriter dengan kekuatan politik yang terkonsentrasi dapat lebih mudah mengelola perubahan besar, seperti penutupan industri bahan bakar fosil dan transisi ke energi terbarukan, meskipun dengan cara yang lebih represif.
China, misalnya, telah berhasil memasarkan teknologi energi terbarukan ke negara-negara berkembang, menjadikannya alternatif utama bagi kerjasama energi dengan negara-negara Barat.
Ini memperlihatkan bagaimana pengaruh geopolitik dapat berperan dalam merancang ulang arsitektur kerja sama internasional mengenai perubahan iklim.
Saat COP29 dimulai, tantangan besar yang dihadapi dunia adalah bagaimana melibatkan negara-negara raksasa minyak ini dalam upaya global untuk mengurangi emisi karbon dan membatasi pemanasan global hingga 1,5 derajat Celsius.
Negara-negara ini, yang masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil untuk pertumbuhan ekonomi mereka, berisiko menghambat kemajuan yang telah dibuat dalam perundingan internasional sebelumnya.
POPULAR
RELATED ARTICLES





